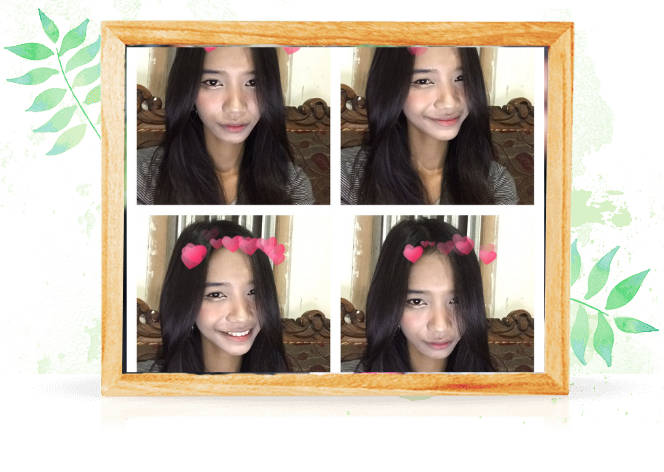Now Playing : Marina and The Diamonds - Savages
“Mengapa manusia cenderung condong ke arah kekerasan?”
“Apakah kita Tuhan yang berhak menghakimi sesama?”
“Kita tidak lebih mulia dari siapapun, karena Tuhan telah menutupi dosa-dosa menjijikkan kita”
Saat ini aku sudah berumur 23 tahun, lebih tepatnya 14 Juni nanti. Banyak hal yang sudah kulalui. Aku menemukan banyak macamnya sifat-sifat manusia yang unik, namun juga mengerikan. Memori lamaku berusaha kembali ke permukaan, saat SMA dulu aku pernah begitu ketakutan dengan yang namanya; bekerja. Namun sekarang, aku begitu menyukai hal tersebut. Lelahku dibayar dengan uang yang akan kugunakan untuk mencukupi kebutuhan, tidak hanya untukku sendiri, namun untuk adik dan ibuku.
Pekerjaan pertamaku adalah sebagai barista di salah satu cafe di Malang saat itu, bulan Februari tahun 2021. Begitu menakjubkannya, bagaimana orang-orang di sekelilingku adalah orang-orang kreatif yang menyibukkan diri mereka, berkecimpung untuk membuat minuman yang dengan harap-harap cemas akan membawa hidup mereka ke masa depan yang lebih baik. Aku sangat bahagia dengan pekerjaan pertamaku saat itu, mencuri ilmu sedikit demi sedikit dari mereka yang pengalamannya jauh lebih banyak dibanding aku.
Di bulan pertamaku, tentu banyak kesalahan yang kulakukan. Dimarahi bos, dimarahi teman satu shiftku yang pada saat itu adalah makanan sehari-hari. Beruntungnya aku, mereka tetap dengan sabar mengajariku sampai aku benar-benar bisa memahami tiap menu yang disajikan, bahkan belajar membedakan tiap bumbu dengan rasa-rasanya yang berbeda namun tetap bisa khas. Aku sangat senang dengan pekerjaan pertamaku ini, aku juga mempunyai banyak sekali relasi dari berbagai macam manusia yang akhirnya kutemui pada saat itu.
Semua berjalan lancar, hingga akhirnya tibalah orang baru di kafe tempatku bekerja saat aku hendak membuka pintu kafe. Ia memarkirkan motornya di samping motorku. Aku baru ingat, ia adalah orang yang akan diposisikan sebagai head-barista, menggantikan yang sebelumnya telah resign. Sebut saja namanya sebagai Boni, seorang perempuan berumur 26 tahun (awalnya aku tidak tahu bahwa ia perempuan, karena fisiknya seperti laki-laki). Otomatis aku menyapanya, karena yang saat itu shift pagi adalah jadwalku.
“Yang mau shift pagi di kafe ‘kan, mas? Salam kenal aku, Lavida” ucapku tersenyum sambil mengulurkan tanganku.
Ia menjabat tanganku, “Iya, salam kenal. Aku Bonita, tapi panggil saja aku Boni,” aku langsung kaget dan sedikit canggung, nada bicaranya begitu lembut.
“Eh maaf, mba” celetukku salah-tingkah membenarkan panggilan. Ia hanya terkekeh pelan, “Gapapa, panggil Boni aja” lanjutnya lalu melepas jabatan tangan kami.
Aku melihat perempuan di belakangnya, berambut panjang, kulit putih, dan mata seperti boneka. “Cantik sekali,” ujarku dalam hati.
Aku mengajaknya berkenalan pula, “Halo, mba. Salam kenal, aku Lavida”.
Tapi perempuan itu terlihat sangat ketus padaku, ia hanya membalas jabatan tanganku singkat dengan senyuman miring, “Iya, aku Puspita”.
“Yaudah, ayo masuk” ajakku pada mereka berdua lalu memasukkan kunci ke knop pintu dan memutarnya. Pintu pun terbuka, kami segera melakukan opening yaitu bersih-bersih kafe dan menyiapkan bahan-bahan yang akan kami gunakan ketika ada pelanggan nantinya.
Beberapa minggu kemudian, aku semakin akrab dengan Boni. Kami memiliki kesukaan yang sama dalam bidang psikologi. Ia juga suka bermain permainan Call of Duty di ponselnya, yang saat itu juga kumainkan. Kemudian terkuak fakta mengejutkan bahwa perempuan cantik yang saat itu dia bawa bukanlah saudara atau sahabatnya, melainkan pacarnya.
“Oh iya, mba cantik yang waktu itu bareng kamu kok udah jarang main ke sini lagi? Kemana?” tanyaku sambil berusaha mengingat petikan gitar sesuai nada yang diarahkan Boni, ia sedang mengajariku cara memainkan gitar saat itu.
“Oh, Puspita. Aku lagi ada masalah sama dia, ‘sih.” jawabnya singkat.
“Loh? Kenapa?” tanyaku penasaran lalu mengalihkan fokusku dari senar gitar pada Boni.
Boni mengangkat bahunya ringan, “Sepertinya dia cemburu padamu, Lav” jawabnya sambil tertawa miris. Aku mengernyit bingung, “Maksudnya?”.
Boni tidak menjawab, ia malah beranjak dari duduknya ke arah bar dan mengambil kantong beans kemudian memasukkannya ke mesin grinder.
“Mau bikin Cappucino?” tanyaku mengikutinya.
“Iya, ‘nih. Sekalian kuajarin latte-art, mau? Kata Mas Tyo, kamu belum bisa nge-latte,” ujarnya sambil merapikan beans yang telah menjadi bubuk kopi dengan temper. Kulihat pergelangan tangannya yang sedang menekan dengan kuat agar bubuk kopi itu menjadi padat, di sekitar lengannya ada gelang tridatu, yang sebelumnya juga pernah kulihat digunakan oleh Puspita. Namun jika Boni menggunakannya di area lengan, Puspita menggunakannya di sekitar pergelangan kaki. Gelang yang sama, juga helm yang mereka gunakan sama, Cargloss, walaupun berbeda warna. Banyak barang couple yang mereka miliki.
Saat Boni sedang meletakkan dua gelas sloki di bawah pancuran Espresso yang sedang mengalir, aku mendekat ke arah Boni agar ucapanku tidak terdengar kawan shift yang lain.
“Kamu sama Puspita… Pacaran?” selidikku dengan wajah penasaran.
Boni akhirnya menatapku, “Iya. Kenapa? Kaget, ya? Kalau mau menjauh, lakukan saja, Lav. Gapapa, aku sudah biasa” nadanya terdengar begitu getir. Suasana canggung, aku terdiam. Ia berbalik badan menuju ke arah dapur, melewatiku begitu saja yang masih diam mematung. Tangannya membuka freezer, hal selanjutnya yang kutahu adalah ia menyodorkanku milk-jug.
“Ayo, aku ajari bikin latte dulu,” lanjutnya membuyarkan syokku.
Aku berusaha tenang dan tersenyum,
“Kenapa aku harus ngejauh? It’s fine with me, Bon” balasku sambil meraih milk-jug yang ada di genggamannya.
Boni tersenyum simpul, “Aku seneng bisa berteman sama kamu, kamu tahu, aku jarang punya teman” ucapnya singkat lalu mulai menarik tuas mesin Espresso untuk memanaskan saluran uap.
“Aku juga, ‘kok. Aman, aku paham” ujarku sembari menuangkan susu Greenfield ke dalam milk-jug. Bonnie memegang tanganku yang sedang memegang milk-jug, dia miringkan sekitar 45°. “Kita steaming dulu susunya, agar nanti bisa muncul gambar di atas espresso.” jelasnya lebih detail. Aku mengangguk, berusaha memahami tiap langkah yang ia ajarkan.
Selama beberapa hari itu, kami cukup dekat sebagai teman shift. Sampai suatu saat, Puspita datang ke kafe dengan langkah tergesa-gesa, ia terlihat marah dengan Boni. Aku tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi sampai Puspita meneriakinya hari itu. Aku tidak terlalu tahu-menahu tentang mereka. Kecuali jika Boni yang memang ingin bercerita, walaupun hanya beberapa bagian saja. Tapi yang dapat kusimpulkan dari cerita Boni, Puspita termasuk perempuan yang mudah tersulut kecemburuan. Bahkan ketika Puspita duduk bersampingan denganku, ia sama sekali tidak menjawab sapaanku atau uluran tanganku lagi, apalagi jika kuajak berbasa-basi, aku seperti sedang berinteraksi dengan tembok.
“Sepertinya memang benar kata Boni, Puspita cemburu padaku” ucapku dalam hati saat melihat mereka berdua memojok di sudut kafe. Terlihat Boni berusaha memberi pemahaman pada Puspita dan meminta maaf. Puspita menyilangkan tangannya kasar saat melihat Boni akan memegang tangannya. Teman shiftku yang lain, namanya Gio mendekat ke arahku.
“Eh, kenapa itu mba Boni dan mba Puspita?” tanyanya penasaran sambil melihat ke arah mereka berdua.
Aku menyeruput kopi di tangan kananku tak acuh, “Entahlah, seperti biasanya mungkin.”
“Cemburu sama lu lagi?” balas Gio mengambil gitar di belakang punggungku lalu duduk di sampingku.
“Mungkin, ga tau. Ga peduli juga,” balasku datar sembari fokus memainkan Call of Duty di ponsel Boni karena saat Puspita secara tiba-tiba datang, Boni sedang match. Di saat itu pula, ia buru-buru berkata agar aku melanjutkan permainannya.
Baru saja, aku akan melampaui satu poin di atas musuhku karena poin kami seri, secara mengejutkan terdengar gebrakan meja dari sudut kafe. Fokusku dan Gio segera teralih pada pasangan tadi, Puspita terlihat sangat marah.
Boni berdiri lalu dengan nada tinggi menjawab, “Udah, terserah maumu. Aku udah capek, pulang aja kamu. Cuma jadi beban buat kerjaanku di sini,”. Mata Puspita memerah menahan amarah, terlihat berkaca-kaca. “Ia akan menangis,” sinis Gio. “Hussh,” balasku berpura-pura tidak menyadari apapun.
Aku pun tetap fokus pada layar ponsel, tapi sialnya karena terganggu, aku kalah. “Sial!” ujarku kesal. Aku merasa seperti ada yang menatapiku, ku arahkan pandanganku kembali ke arah mereka berdua, Puspita sedang menatapiku tajam. Terlihat sekali ia sangat membenciku. Aku memberinya senyum, namun ia malah melengos pergi tanpa sepatah katapun.
Boni duduk di tengah-tengah antara aku dan Gio. Gio mengawali pembicaraan,
“Udah, mba. Masih mau diterusin? Udah toxic gitu,” ucap Gio sambil memetik gitar, mencari nada yang pas. Boni tersenyum getir lagi, “Udah biasa kayak gitu,”. Aku diam saja, masih fokus memilih senjata dalam permainan dan memperbaiki layoutnya agar sesuai dengan jariku.
“Kali ini masalahnya apa?” cecar Gio.
“Karena Lav pakai ponselku,” ujar Boni sambil tertawa. Gio ikut tertawa. Aku menatap mereka berdua dan segera melempar ponsel itu kepada pemiliknya. Beruntung Boni sigap menangkapnya.
“Hah? Apa yang perlu dicemburuin dari pakai ponselmu untuk main game?” ujarku frustrasi.
“Iya, karena dia ga kubolehin buka ponselku sembarangan. Tadi pas baru masuk terus lihat kamu pakai ponselku dengan santainya, juga keliatan seru banget, dia ga suka. Maafin ya Lav,” jawab Boni kemudian menyalakan rokoknya yang ada di atas meja.
“Santai, ‘sih. Cuma ya, kenapa harus aku yang selalu dibawa-bawa? Padahal aku hanya hidup dan bernapas seperti orang normal lainnya, melakukan aktivitas normal” aku mengernyitkan dahiku, sesekali menyeruput kopi tadi yang mulai dingin.
“Karena emang lu sering bikin emosi aja sih, Lav. Ga ngapa-ngapain juga lu selalu bikin gua emosi,” jawab Gio mengusil.
“Dih, anak kampret” balasku berdecih.
Saat jam menunjukkan pukul setengah sembilan malam, yang lainnya bebersih untuk closing. Sedangkan aku bagian menghitung penjualan hari ini karena aku memegang kasir seharian.
“Minus dua puluh ribu,” ucapku lalu menghela napas kasar.
Kebetulan Boni yang mencuci di wastafel menghampiriku, “Hitung lagi, siapa tau notanya ada yang salah input”.
Aku pun menghitung penjualan dari tiap nota dan berusaha mengingat-ingat biaya apa saja yang sudah keluar hari ini, masih tidak ketemu. Gio pun membantu, masih pula tidak ketemu. Kami bertiga pasrah kemudian patungan untuk mengganti dua puluh ribu yang tidak ketemu tadi.
Gio memakai jaketnya dan memberikan kunci kafe padaku, “Besok lu shift pagi ‘kan?”.
Aku mengangguk dan mengambil kunci kafe, kumasukkan ke kantong jaketku.
“Gua duluan ya Lav, mba…” pamit Gio pada kami berdua.
“Iya, duluan aja. Hati-hati, Yo.” ucapku sembari bergegas memasukkan barangku yang tercecer di meja ke dalam tas.
Boni mendekat dan membantuku mengemasi barang, “Santai aja, lho. Kenapa buru-buru banget?”.
“Takut setan, di sini serem tau” balasku masih panik.
“Kan ada aku, eh… Maksudmu, aku setan?” canda Boni tapi ia malah santai duduk di sofa, kemudian membakar rokoknya.
“Bukan gitu, dari cerita Gio, di sini kalau di atas jam 9 malem banyak setannya,” aku memakai tasku lalu menaikkan topi hoodie pinkku. Aku berdiri, berdecak.
“Kamu ga pulang? Ayo balik,” ujarku.
“Nanti dulu, aku lagi males balik. Puspita nunggu aku di depan kosku, aku lagi ga pingin ketemu dia. Temenin di sini bentar, bisa?” pintanya padaku lalu menepuk tempat duduk di sampingnya. Aku menghela napas.
“Baiklah, sekali ini aja, ya. Omku bisa marah kalau aku pulang di atas jam 10 malam,” terangku padanya. Saat itu aku tinggal di rumah Om dan Tanteku yang berada di Singosari, mereka lebih posesif daripada orangtua asliku.
“Iya. One smoke?” tanyanya memastikan. Aku menatapnya kesal,
“Allright, one smoke.” aku pun duduk di sampingnya.
Tidak terasa kami berbicara, tertawa, main game bersama, menyanyi, sampai alarm skincareku berbunyi. “Jam setengah sebelas!” jeritku panik. “Sialan, habis aku dimarahi omku!” lanjutku. Boni terlihat khawatir, “Sudah, izin saja pada mereka kalau kamu menginap di rumah teman. Menginap di kosku saja, bagaimana? Puspita juga mungkin sudah tidak menunggu lagi. Bahaya jika kamu ke Singosari jam segini,” nasihatnya. Aku dilema. Akhirnya aku pasrah saja.
“Okay, ya sudah. Ayo balik,” ajak Boni. Aku pun mengikutinya dan kami berjalan beriringan dengan motor menuju ke kosnya yang hanya 10 menit dari kafe.
Sesampainya di kosnya, aku langsung terlelap karena saking lelahnya. Padahal saat itu Boni akan membuatkanku susu hangat karena udara di luar sangat dingin saat perjalanan. Belum sempat membersihkan kaki atau muka, dan saat Boni kembali ke kamar membawa susu hangat, ia melihatku sudah masuk ke alam mimpi. Tengah malam aku terbangun, selimut hanya satu dan itu hanya menutupi tubuhku. Aku melihat ke belakangku, Boni tidur tanpa selimut dan bantal. Tiba-tiba ia bergerak dan memelukku. Aku segera menjauh dari Boni dan tidur di pojok sudut kamarnya.
“Dia orang yang baik, tapi aku takut” ujarku dalam hati kemudian melanjutkan istirahatku.
Paginya, tiba-tiba aku terbangun karena dobrakan pintu kamar. Boni yang terkejut, langsung bangun dari tidurnya. Ia berdiri, berjalan sempoyongan berusaha mengembalikan nyawanya. Ia keluar kamar dan mengejar seseorang, “Puspita!” teriaknya yang mulai jauh dari indra pendengaranku. Aku menghela napas berat, “Pasti akan terjadi salah paham lagi,” sedihku.
“Ngapain ada perempuan itu di kos mu? Kalian habis ngapain, hah?” jerit Puspita yang kesal terdengar sampai kamar.
“Itu lho, dia kemarin udah kemaleman pas closing. Rumahnya di Singosari, aku ga tega! Lagipula kamu lihat sendiri tadi tidurku sama dia jauh-jauhan, ‘kan?” terdengar sayup-sayup suara Boni membela dirinya.
Aku memutuskan untuk tetap cuek. Memposisikan diriku untuk duduk dan menyenderkan punggungku pada sudut dinding. Aku meng-cek ponselku, banyak pesan masuk. Aku membalasnya satu-persatu, beberapa dari Ibuku yang di Madiun, menanyakan kabar. Yang lainnya, berasal dari teman-temanku yang menanyakan apakah nanti malam aku memiliki waktu luang untuk main. Ketika jemariku sibuk menari-nari di atas keyboard ponselku, Puspita dan Boni kembali. Aku berusaha untuk terlihat normal, dengan wajah acak-acakan dan kelelahan, aku tersenyum menyapa. “Hai, dari mana?” tanyaku ramah dengan suara serak akibat baru bangun dari tidur.
“Dari rumah, Lav” jawab Puspita akhirnya lalu duduk di depanku.
“Are you okay?” tanyaku, karena matanya terlihat sembab.
“Aku okay, kok.” jawabnya singkat berusaha tersenyum, namun aku bisa melihat bahwa hal itu palsu.
“Perempuan secantik kamu ga pantes sedih, cantiknya hilang nanti” aku menggoda. Puspita tertawa kecil. Tiba-tiba Boni melempar sikat gigi, “Kamu ga bawa alat mandi, ‘kan? Pakai itu, sikat gigi baru. Odol dan sabunnya sudah ada di kamar mandi bawah, handuknya pakai yang warna merah. Itu baru saja kucuci,” jelas Boni padaku. Aku tersenyum, “Thank you, aku mandi dulu” lalu berlari menuruni tangga. Setelah aku mandi dan keramas, kepalaku terasa lebih ringan. Aku melihat Boni dan Puspita di dalam kamar sedang bercanda bersama, “Cie, udah baikan. Gantian mandi dulu sana, Bon. Keburu telat absen ntar,” godaku pada mereka. Mereka terlihat malu-malu. Boni segera menyiapkan baju ganti yang akan ia bawa ke kamar mandi.
Puspita tersenyum padaku, aku membalas senyumannya. “Nah, kamu kalau senyum gitu cantik banget, sumpah” aku memuji Puspita tulus.
Senyum Puspita semakin melebar, terlihat gingsulnya yang membuatnya terlihat semakin imut. “Maaf ya Lav, aku sempat salah paham sama kamu” ia membuka pembicaraan.
Aku terkekeh kecil, “Santai, aku udah ga peduliin itu, ‘kok”.
Kemudian aku menatap Boni, ia ketahuan melihati kami berdua bergantian dengan tatapan yang sulit diartikan. “Apaan liat-liat? Mandi sana,” ujar Puspita lalu melemparkan batal pada Boni, mengusirnya. Giliran aku yang tertawa melihat kelakuan mereka.
Semenjak hari itu, aku memiliki teman tambahan, Boni dan Puspita. Saat uang bulanan dan gajiku kurang untuk makan dan bensin, mereka dengan sukarela membiarkanku tidur di kos Boni dan membuatkanku makanan pula. Aku bersyukur mengenal mereka.
Pasangan yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang karena mereka memiliki gender yang sama. Banyak yang mungkin akan merutuki pasangan ini, dianggap tidak normal dan menyalahi aturan. Tentu saja, memang sepatutnya laki-laki diciptakan berpasangan dengan perempuan, begitupun sebaliknya. Namun, mereka tetaplah manusia yang sama seperti kita. Mereka akan menangis jika tersakiti, akan tersenyum saat bahagia. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang membedakan derajat kita hanyalah iman kita kepada Tuhan. Banyak temanku yang menyukai sesama gender namun shalat mereka lebih rajin daripada aku, puasa Senin-Kamis, bahkan sampai melakukan tahajjud. Tidak ada yang ingin dilahirkan berbeda. Mereka juga seseorang yang ingin diperlakukan baik oleh sekitarnya.
Bukan, bukan maksudnya aku membenarkan perilaku tersebut. Aku hanya mencoba memanusiakan manusia. Tentang dosa dan pahala, biar itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan-Nya. Asalkan mereka tidak memaksa kita untuk ikut ke dalam komunitas mereka, menurutku mereka akan tetap mendapat rasa hormatku sebagai sesama manusia. Apakah aku sudah sesempurna Nabi? Setinggi Allah? Sampai-sampai aku bisa berani menghakimi seseorang, bahkan sampai menyakitinya secara fisik? Tidak. Aku pun jauh dari sempurna, selama ini Allah hanya terlalu baik padaku. Ia menyembunyikan aib-aibku dengan sangat rapat, alhamdulillah.
Terlebih pada yang mengganti kelaminnya, atau biasa disebut transgender (waria). Mereka mengalami kekerasan yang paling parah dengan frekuensi yang sangat tinggi. Berdasarkan jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 No. 02 tentang Heteronormativitas, Wacana LGBT dan Perjuangan Komunitas Waria Melawan Stigma bahwa waria yang termasuk dalam kelompok T (Transgender) merupakan kelompok paling rentan menerima kekerasan karena penampilan fisik mereka yang lebih kentara dibanding kelompok LGB. Ketidakselarasan tubuh dan perilaku ini membuat waria dianggap aneh dan tereksklusi dari masyarakat melalui konstruksi stigmatisasi yang bersifat homophobia. (Inestya Kartikaningdryani, 2019).
Apakah kalian ingat kasus tentang Ryan Jombang?
Ini merupakan salah satu kasus yang sempat menjadi trending topic di seluruh penjuru negeri saat itu. Ia merupakan salah satu anggota komunitas LGBT di Indonesia. Namun ia bukannya mencoba untuk berubah menjadi lebih baik dan meminta pengampunan agar dikembalikan ke jalan yang benar, ia malah semakin keluar jalur dan nekat menjadi pembunuh. Kasusnya yang paling mengerikan adalah ketika ia membunuh salah satu korbannya bernama Heri Santoso, dengan memutilasi badannya menjadi beberapa bagian agar tidak diketahui polisi. Setelah ditelisik lebih dalam, pembunuhan ini diakibatkan kecemburuan Ryan terhadap Heri yang rela mengeluarkan uang agar bisa merasakan hubungan badan dengan pacar Ryan bernama Noval.
Ketika namanya menjadi viral, Ryan mengaku pernah mendapatkan penganiayaan dari Habib Bahar bin Smith. Ia dihajar habis-habisan sampai muntah darah terus-menerus. Mereka bisa bertemu karena berada di dalam sel penjara yang sama, di Lapas Gunung Sindur. Kejadian bermula ketika Ryan hendak berangkat ke masjid untuk shalat Dhuhur, secara tiba-tiba ia dipanggil oleh kumpulan massa Habib Bahar. Mereka membawa senjata tajam, Ryan diinjak-injak, ditendang, hingga ia terus-menerus memuntahkan darah.
"Dia membawa pedang yang sangat panjang, saya diancam kalau sampai melawan saya dibunuh. Saya diinjak, ditendang habis-habisan sampai saya muntah darah terus," ucap Ryan. Perseteruan antara Ryan Jombang dan Habib Bahar bin Smith tersebut memunculkan cerita yang berbeda. Menurut Ryan, Habib Bahar memiliki utang-piutang, sedangkan versi Habib Bahar, Ryan Jombang mencuri uangnya.
Naasnya, banyak petugas yang melihat Ryan dihakimi secara mengenaskan saat itu namun tidak ada yang membantunya. Mereka hanya diam melihat Ryan disiksa oleh banyak massa. Memang Ryan merupakan seorang pendosa, namun tidak semestinya kita menghakiminya seperti itu. KITA. BUKAN. TUHAN.
Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 146,
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ
Artinya: “Allah mencintai orang-orang yang sabar,”
Kemudian ditambah dengan:
Surat An Nahl ayat 126
وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖۗ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ
Artinya: "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar."
Ingat, ‘kah kalian dengan kasus yang menimpa seorang Ayah yang memaafkan pembunuh anaknya tahun 2017? Ia adalah seorang ustadz, bernama Ustadz Jitmoud. Beliau sangat inspiratif menurutku. Ada satu kalimat dari beliau yang akan selamanya tertato jelas dalam ingatanku tiap kali ingin marah pada seseorang,
“Aku tidak menyalahkanmu, aku menyalahkan setan!” ucapnya dengan nada bergetar. Kemudian di persidangan ia memeluk pelaku pembunuh dan perampok anaknya saat anaknya bekerja mengantar pizza.
“Jika Salahuddin ada disini dalam keadaan hidup di akan memaafkanmu karena demikian lah dia," kata ustaz Jitmoud pada Trey, sang pelaku saat di persidangan.
Sungguh mulia hati beliau, semoga kita senantiasa diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi amarah dalam diri kita. Agar tidak ada kekerasan dan korban-korban lainnya, karena kejahatan itu menular. Boleh saja untuk waspada, namun tetap berpikir sebelum bertindak.
Satu kasus lagi, ingat dengan kasus di Indonesia, kasus vigilantisme paling menyedihkan sepanjang aku membaca berita-berita sejauh ini? Kisah tentang seseorang yang dituduh mencuri amplifier masjid? Istrinya sedang mengandung anaknya yang berusia 6 bulan saat itu. Suaminya, bernama Muhamad Aljahra atau biasa dipanggil juga dengan Zoya, dibakar hidup-hidup oleh ramai-ramai manusia, padahal belum tentu ia terbukti mencuri. Ia adalah laki-laki yang berprofesi sebagai tukang reparasi elektronik kala itu. Tindakan gegabah tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak bersalah, seorang kepala keluarga yang menjadi tiang pondasi bagi keluarga kecilnya.
Begitu menyedihkannya. Kekerasan bukanlah jawaban. Mari bersama-sama membenahi luka dalam diri kita. Semua emosi yang kita keluarkan berlandaskan dari luka busuk yang tidak pernah kita berusaha sembuhkan.
ِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم
Semoga kita berhasil menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain.